Perhelatan politik di tahun 2019 ini cukup menarik dan berbeda dari perhelatan sebelumnya, karena melibatkan peran aktif ulama dalam penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ada yang maju sebagai calon wakil presiden, ada pula yang membuat “ijtma’ ulama” untuk menentukan arah atau pilihan sebagian ulama untuk mendukung salah satu paslon.
Sepanjang sejarah, peran ulama memang cukup sentral di dalam pemerintahan umat Islam. Bukan hanya sebagai pemimpin atau pemuka agama, mereka juga mengambil peran yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Di Indonesia khususnya, para ulama cenderung bervariatif dalam menentukan langkah perjuangannya; mendukung secara langsung salah satu paslon atau menempuh jalan lain yaitu menjadi oposisi. Dalam INSISTS Saturday Forum (INSAF) pekan lalu (12/1), bertajuk “Ulama dan Politik: Apa Masalahnya?”, Peneliti Senior INSISTS Dr. Syamsuddin Arif, MA menunjukkan sumber normatif sekaligus historis tentang pandangan dan keterlibatan ulama di bidang politik.
Istilah ulama dalam Al-Quran disebut sebanyak dua kali, yakni pada surat Al-Fathir (28) dan Asy-Syua’ra (197). Secara harfiah, ulama berarti orang yang berilmu. Berakar dari kata ‘a-li-ma, jika tunggal maka ‘aliimun (sangat mengetahui) yang merupakan superlatif dari ‘aalimun (mengetahui). Dalam berbagai tafsir, diartikan bahwa ulama (al-‘ulama’u) berarti orang yang takut kepada Allah. Ulama dalam pandangan Ibn Taimiyyah memiliki tiga elemen dalam diri, yakni ilmu, iman, dan rasa takut hanya kepada Allah. Tidak semua orang yang berilmu takut kepada Allah, namun semua yang takut kepada Allah sudah pasti berilmu.
Murid beliau, Ibn Qayyim al-Jauziyah, juga mendefinisikan ulama sebagai orang yang berilmu, ahli hadist dan ahli hukum (fiqh/syariah) serta pemegang otoritas (ulul amri). Dalam Islam, otoritas secara hierarkis dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya, diikuti ulama, dan terakhir umara’ (pemerintah), sehingga otoritas pemerintah dan politisi sebenarnya berada di bawah para ulama. Namun gelar ulama sendiri tida diperoleh dari lembaga, pesantren, atau perguruan tinggi, akan tetapi dari pengakuan dan kesaksian dari sesama ulama lain. Orang yang berilmu sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dengan menunjukkan bukti yang kuat. Imam al-Qurtubi mengajukan definisi sejenis bahwa ulama adalah orang yang berilmu dan paham akan Kitab Suci.
Dari definisi tersebut, kita bisa melihat bahwa peran ulama cukup berat sehingga tak sembarangan orang mampu menanggungnya. Orang yang masih mengikuti hawa nafsu dan mengikut-ikuti orang lain dengan tanpa bukti, tak dapat dikategorikan sebagai ulama. Hal ini juga berkaitan dengan peran besar yang dipegang ulama sebagai pewaris Nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, misalnya, berperan sebagai pemberi peringatan di hadapan penguasa yang zalim. Begitu pun Nabi Muhammad sebagi kepala negara saat di Madinah, dilanjutkan dengan para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin.
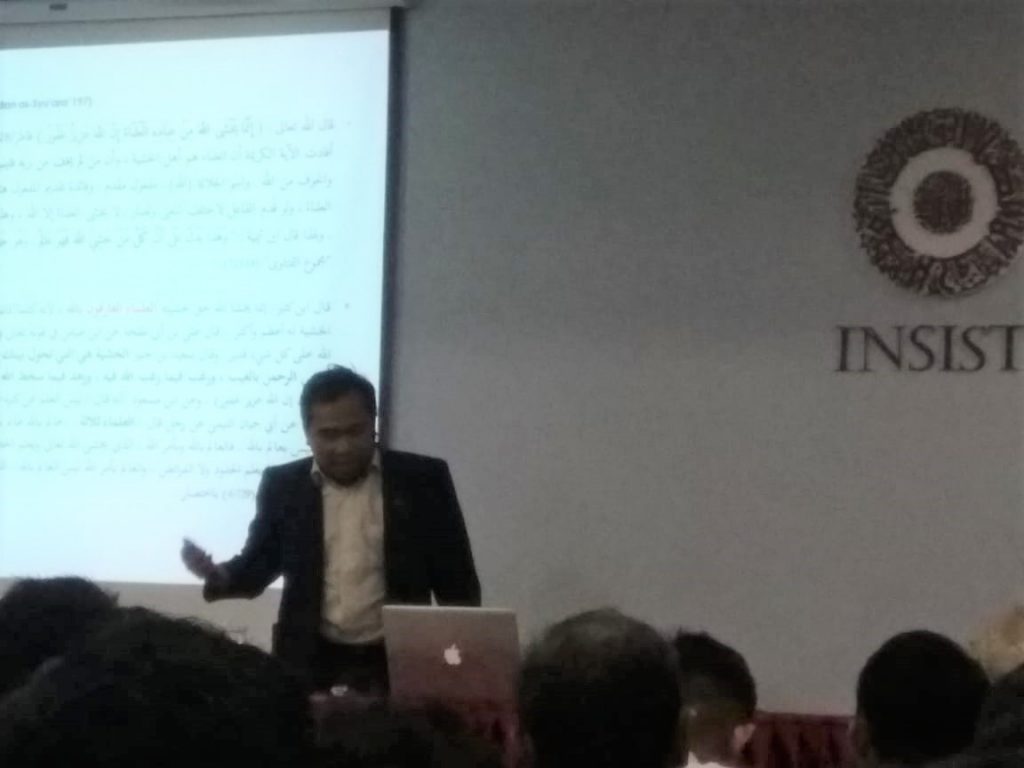
Imam Ahmad Ibn Hanbal merumuskannya ke dalam lima peran utama, yakni dakwah (yad’uuna), resistensi/sabar (yashbiruuna), revival/menghidupkan (yahyuuna), membuka mata (yabshiruuna), dan menegasikan/destruktsi atas ekstrimisme dalam segala hal (yanfuuna). Kaitan peran tersebut di dalam sejarah politik umat Islam terlihat dalam posisi antara ulama dan penguasa, yang dapat berdiri sebagai oposisi (mengkritik), koalisi (bekerjasama), dewan ahli (penasehat), dan pelaku politik itu sendiri.
Umat Islam sejak awal sejarahnya sudah terlibat di dalam pemerintahan, legislasi (pembuatan kebijakan), dll. Survei pengaruh Islam dalam Politik tahun 2011 oleh Pew Research Center menunjukkan, sebagian besar muslim Indonesia menerima demokrasi, yakni 91% di samping penolkaan sebesar 6%. Survei tersebut juga menunjukkan, meski setuju dengan demokrasi, mereka tidak menolak syariat sebagai hukum, sehingga koeksistensi Islam dan syariat memang berjalan beriringan.
Penulis : Isna Nur Fajria, Rizqi Fadhila, Syaidina Sapta Wilandra
Penyunting : Ismail Al-‘Alam






